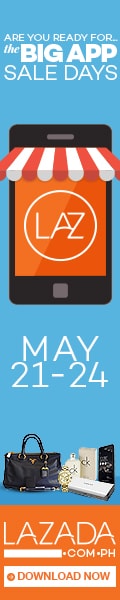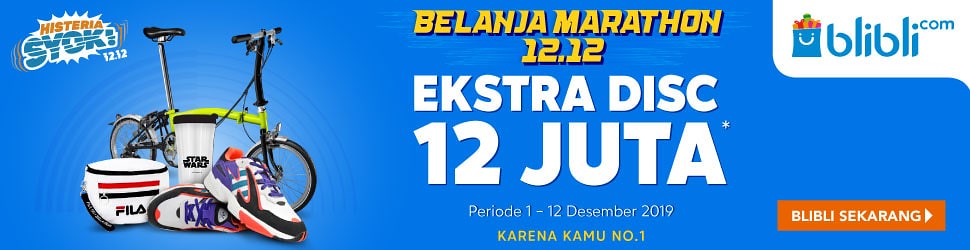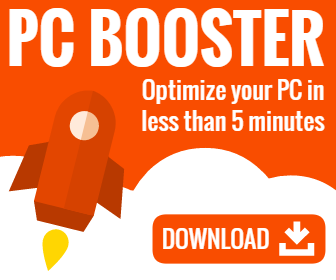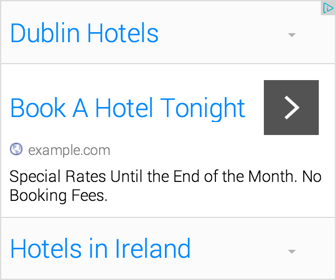Oleh: Jaya Putra
Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan teknologi tidak mengikuti regulasi baru mengenai kewajiban pendaftaran.
Namun, kebijakan itu justru memantik kemarahan publik. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan dengan penjarahan dan bentrokan meluas. Otoritas Nepal melaporkan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Gelombang protes kemudian berkembang menjadi tuntutan antikorupsi, hingga memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Situasi ini menunjukkan betapa cepatnya krisis politik bisa dipicu oleh kebijakan yang menyentuh ruang digital.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera bergerak memastikan keselamatan warga negara Indonesia di Nepal. Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, menegaskan tidak ada laporan WNI yang terdampak langsung kerusuhan.
Judha menjelaskan bahwa terdapat 57 WNI yang tinggal di Nepal, 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu, dua personel TNI yang tengah menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan asal Indonesia. Seluruhnya dipastikan aman, meski tetap diimbau menjauhi kerumunan dan mengikuti informasi resmi pemerintah.
Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Nepal adalah bahaya informasi palsu atau hoaks yang kerap menjadi pemantik ketegangan. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengingatkan bahwa separuh dari pengguna internet di Indonesia terpapar hoaks.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai situasi ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, hanya sekitar 20–30 persen masyarakat yang mampu membedakan informasi benar dengan yang palsu, sementara sisanya rawan menjadi korban manipulasi.
Ia menambahkan bahwa penyebaran hoaks kini semakin berbahaya dengan adanya teknologi kecerdasan buatan. Video deepfake dan konten manipulatif lain menyebar cepat di dunia maya, dan tidak sedikit orang mempercayainya tanpa proses verifikasi.
Penyebaran informasi semacam itu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan upaya pemerintah atau media untuk melakukan pemeriksaan fakta. Karena itu, Komdigi sedang menyusun peta jalan kecerdasan buatan agar ada etika dan aturan yang jelas dalam penggunaannya, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak negatif.
Ancaman hoaks bukan hanya soal kesalahpahaman informasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk intervensi eksternal. Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, menilai pola agitasi yang masif di media sosial sering kali menunjukkan adanya peran asing.
Menurut Rasminto, narasi yang diproduksi dan disebarkan di berbagai kanal digital kerap dipelintir untuk menimbulkan keresahan, meskipun tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia melihat adanya grand design pihak luar yang tidak menginginkan Indonesia tampil sebagai negara damai dan maju.
Lebih jauh, Rasminto menegaskan bahwa intervensi asing kini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer, melainkan perang informasi. Manipulasi ide, infiltrasi isu sensitif, dan pengaburan fakta digunakan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Kondisi ini disebut sebagai kolonialisme gaya baru, yang tidak lagi menaklukkan wilayah, tetapi berusaha menguasai kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam provokasi yang dibuat secara sistematis.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa persatuan bangsa menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Ia telah memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, hingga parlemen untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat, termasuk kalangan mahasiswa. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan melalui kekerasan.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya bisa berjalan jika stabilitas tetap terjaga. Oleh karena itu, media massa diharapkan berperan aktif menjaga suasana kondusif dengan mengedepankan pemberitaan yang menumbuhkan persatuan. Pada saat yang sama, masyarakat juga dituntut untuk bijak dalam menyikapi arus informasi yang beredar, agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
Krisis di Nepal seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia. Ledakan informasi yang tidak terkendali di ruang digital dapat dengan cepat berubah menjadi kekacauan politik di dunia nyata. Indonesia beruntung memiliki pemerintah yang sigap melindungi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri, serta serius membangun regulasi untuk menghadapi tantangan digital. Namun, keberhasilan menghadapi ancaman hoaks tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, melainkan juga pada kesadaran kolektif masyarakat.
Jika bangsa ini mampu menjaga persatuan, meningkatkan literasi digital, dan tetap setia pada kepentingan nasional, maka berbagai bentuk provokasi, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak akan mudah menggoyahkan fondasi negara. Indonesia harus menjadikan pengalaman Nepal sebagai cermin, bahwa kehati-hatian terhadap hoaks adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas dan masa depan yang lebih baik.
)* Pengamat Hubungan Internasional